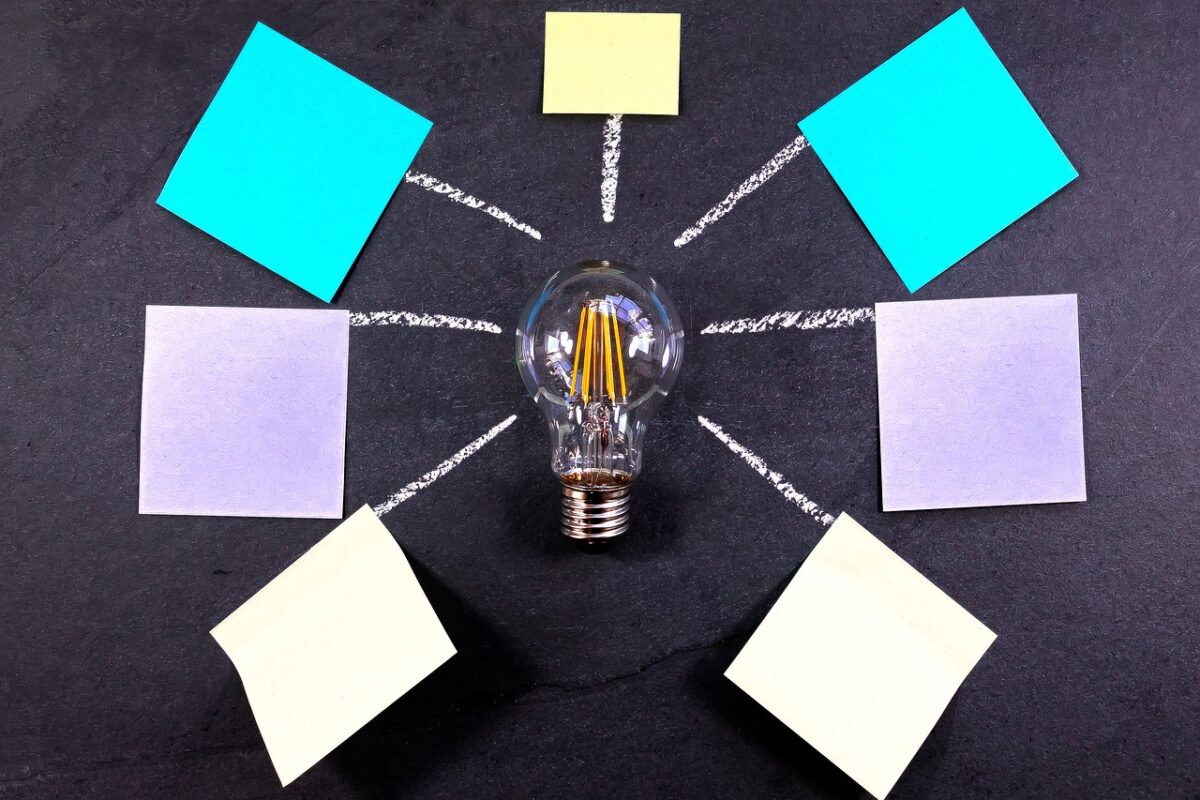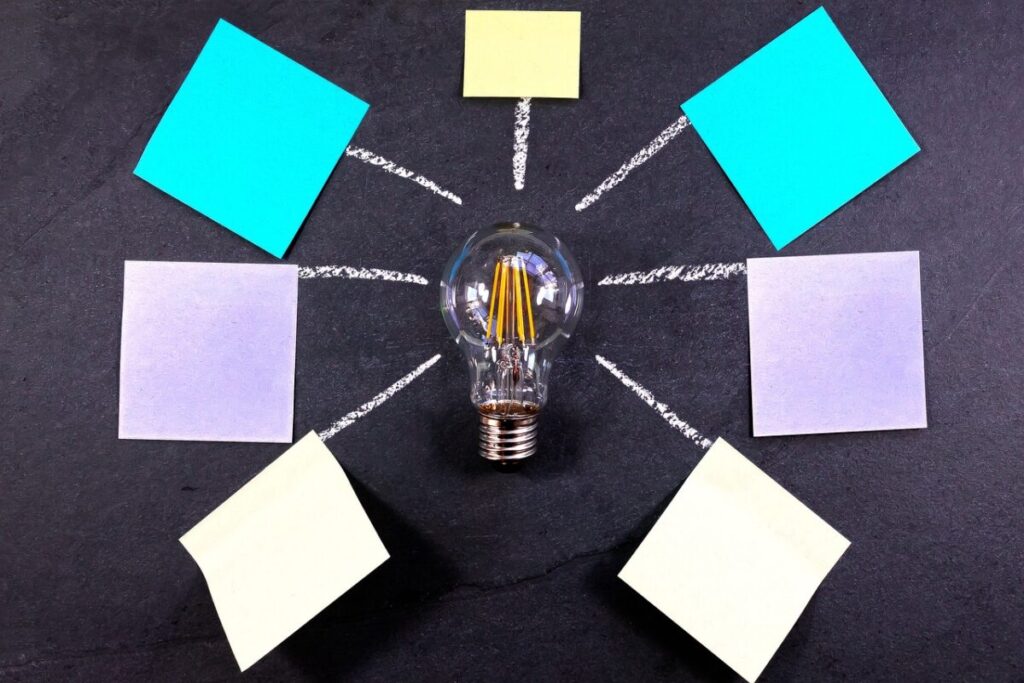
Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram
Langgan Sekarang
Muhammad Yusra bin Ahmad Hulaimi
Kini masyarakat moden lebih peka terhadap kepelbagaian idea. Betapa tidak, para pelopor idea yang pelbagai saling merebut pengaruh dan perhatian masyarakat awam. Di samping kepelbagaian idea ini, kita juga semakin peka terhadap kebebasan untuk berpegang pada idea yang dipilih.
Menurut sebahagian besar ahli masyarakat, kebebasan merupakan syarat yang memaknakan pilihan idea dan moral manusia. Jika seseorang itu menemukan kebenaran dan melakukan amalan makruf tanpa paksaan, maka pujian dan ganjaran layak baginya. Jika dia memilih kebatilan dan melakukan perkara mungkar dengan kerelaan sendiri, maka celaan dan hukuman selayaknya diberikan kepadanya. Oleh itu, banyak yang berpendapat bahawa idea dan pilihan moral seharusnya diberikan kebebasan platform. “Idea lawan idea”. Falsafahnya ialah kebenaran pasti akan menggulingkan kebatilan dengan sendiri.
Dalam sebuah dunia yang ideal, pendekatan idea lawan idea mungkin akan menjadi. Malangnya, pendekatan ini sebenarnya tidak praktikal baik untuk menemukan kebenaran mahupun membungkam kebatilan dalam dunia moden. Hal ini demikian kerana budaya perdebatan idea dan moral masyarakat moden dilatari oleh gejala emotivisme. Menurut ahli falsafah moral Alisdair MacIntyre (1929 hingga kini), melalui gejala ini nilai kebenaran dan moral dikelirukan dengan perasaan sendiri. Banyak yang berasakan bahawa idea dan nilai pegangannya benar, tetapi mereka tidak sebenar-benarnya tahu dan mampu menghujahkan kebenaran pegangannya itu.
Berkenaan dengan suasana ini, MacIntyre memerihalkan dalam bukunya, After Virtue (1984) bahawa kini idea besar dan moraliti sudah kehilangan makna. Apa-apa yang kita ungkapkan sebagai kebenaran, keadilan, maruah, kemanusiaan dan lain-lain nilai hanyalah hamburan kata-kata kosong. Apa-apa sahaja tujuan material seperti keberkesanan komersial, pengaruh politik dan imej diri di ruang awam boleh diputar-belit mengikut kehendak dan perasaan sendiri untuk kelihatan “bermoral”. Akibatnya, pertelingkahan yang melibatkan pendapat moral tidak dapat diselesaikan secara rasional kerana sentiasa ada hujah untuk mana-mana pendapat sekalipun.
MacIntyre memberikan contoh, iaitu setiap orang berhak ke atas badannya sendiri. Oleh itu, seorang ibu yang mengandung misalnya, berhak untuk menggugurkan kandungannya ataupun tidak. Namun begitu, membunuh merupakan kesalahan besar dan menggugurkan kandungan bermakna membunuh janin. Maka itu, menggugurkan kandungan merupakan suatu kesalahan besar. Pada akhirnya, yang manakah harus diutamakan? Kebebasan dan hak pemilikan badan sendiri, atau nyawa kandungan? Di sini, nilai kebebasan (dan pemilikan badan sendiri) bercanggah dengan nilai kemuliaan nyawa. Di dunia Barat, perdebatan ini masih tidak menemukan sebarang penyelesaian dan selalunya kebebasanlah yang dimenangkan.
Persoalannya, dari manakah puncanya gejala emotivisme ini? Menurut MacIntyre lagi, gejala tersebut bermula dengan Zaman Pencerahan Eropah pada kurun ke-17 hingga kurun ke-19 yang mengangkat idea kebebasan sebagai prinsip tertinggi sehingga sering kali menindas prinsip lain seperti keadilan, keselamatan dan kebenaran. Hal ini demikian kerana kebebasan mengizinkan setiap individu untuk memilih sistem moral untuk dirinya sendiri. Mereka berhak memilih untuk berpegang pada keselamatan sebagai nilai tertinggi, atau keadilan sosial, kesaksamaan ekonomi dan kesetaraan gender bukan kerana terbukti secara rasional sebagai nilai tertinggi. Sebaliknya, pegangan mereka sah kerana mereka bebas untuk berpegang dengannya.
Pada hakikatnya, pemerhatian MacIntyre ini dapat diperhatikan juga dalam ruang perbahasan agama Islam. Di satu sudut, golongan Ahli Sunah Waljamaah mengutamakan autoriti tradisi keilmuan Islam yang berpandukan al-Quran dan sunah sebagai panduan untuk memahami dan mengamalkan agama. Di satu sudut lain, golongan yang menggelari diri mereka “progresif” mengutamakan kebebasan berfikir sebagai penawar kemunduran umat Islam.
Sebagaimana masyarakat sekular, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas (1931 hingga kini) dalam Risalah Kaum Muslimin (1970-an) berpendapat bahawa masyarakat Muslim moden juga sedang dilanda dengan gejala yang hampir sama, iaitu kejahilan agama dan kelunturan adab (loss of adab). Jika di Barat emotivisme berleluasa, di dunia Islam loss of adab bermaharajalela. Jika di Barat masyarakatnya keliru akan nilai dengan perasaan sendiri, di dunia Islam masyarakat Muslim keliru akan kebenaran dengan pendapatnya sendiri dalam hal agama. Autoriti ulama bukan sahaja sering kali diketepikan, malah tidak lagi dihormati selayaknya.
Lalu, mengapakah pendekatan “idea lawan idea” tidak akan berkesan? Terdapat empat sebab terjadinya perkara demikian. Pertama, menurut teori moral moden, memahami nilai moral menuntut seseorang itu bersifat rasional. Namun begitu, pemerhatian Benjamin Ginsberg, seorang penganalisis politik Amerika Syarikat, dalam The Captive Public: How Mass Opinion Promotes State Power (1986) menunjukkan bahawa sungguhpun sifat rasional sememangnya merupakan sifat asasi manusia secara amnya, hakikat yang menyedihkan ialah banyak tidak mampu benar-benar berfikir dan bertindak dengan rasional. Seperti yang dijelaskan oleh MacIntyre, manusia mampu menghasilkan pelbagai hujah rasional yang pada hakikatnya menyokong kehendak dan perasaan sendiri.
Imam al-Ghazali menyebut dalam Ihya’ ‘Ulum al-Din bahawa dalam konteks masyarakat yang amat kurang penghayatan tasawuf amatlah mudah untuk nafsu menyembunyikan dirinya di sebalik hujah yang disulam oleh akal, tanpa disedari oleh tuan badan sendiri. Hal ini lebih-lebih lagi benar berhubungan dengan masyarakat moden. Banyak perdebatan hari ini tidak dilatari dengan keikhlasan dan keinginan sebenar untuk menemukan kebenaran. Sebaliknya, emosi, ego dan kepentingan peribadi yang menguasai.
Berhubungan dengan hal ini, kita harus fikirkan bahawa “siapakah yang lebih layak untuk dirujuk?” Ratusan ribu ulama sepanjang zaman yang terlatih dalam pelbagai bidang untuk mentafsirkan agama dan yang tidak dicemari niat dan matlamat kepentingan peribadi atau para pemikir moden yang didanai dengan anasir luar? Antara kedua-dua pihak ini, yang manakah lebih terjamin selamat daripada pengaruh emosi, ego dan kepentingan peribadi?
Sebab kedua yang tidak memungkinkan keberkesanan pendekatan “idea lawan idea” ialah, menurut Noam Chomsky (1928 hingga kini) dalam Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), demokrasi yang membentuk dunia politik moden tidak membenarkan kewujudan platform ilmu yang benar-benar neutral sehingga kebenaran boleh menang dengan sendiri. Kebenaran yang tidak tersusun boleh ditumbangkan oleh kebatilan yang terancang. Dalam dunia demokrasi ini, rencana tersusun yang didanai oleh pelbagai pihak luar untuk menegakkan idea asing lebih banyak. Jutaan ringgit disalurkan untuk memastikan ahli politik memenangi perlumbaan meraih undi dan pertembungan idea. Idea mereka memonopoli minda dan undi orang awam bukan kerana benar, tetapi olahan media yang menyolekkan idea tersebut sehingga kelihatan indah.
“Pembaharuan”, “pengolahan semula”, dan “analisis kritikal” dipaksakan ke atas idea lama dan “konservatif” yang sudah terbukti kebenaran dan keberkesanannya selama ratusan tahun. Kerap kali “analisis kritikal” yang kononnya dilaksanakan itu bersifat tidak cermat dan gopoh. Kebanyakan “ahli” yang mengkaji dan mengkritik pemikiran Islam ini pada hakikatnya tidak memiliki kepakaran dalam bidang yang kononnya dikaji oleh mereka. Demikian pemerhatian yang dibuat oleh Wael Hallaq (1955 hingga kini) dalam Shari‘ah: Theory, Practice, and Transformation (2009).
Ketiga, tahap ilmu dan rasionalistik dalam kalangan orang awam adalah rencam. Begitu juga dengan kebenaran; semakin tinggi tahap sesuatu kebenaran, maka semakin rumit darjah pembuktiannya. Misalnya, untuk mendakwa bahawa para ulama dipengaruhi wacana patriarki yang dominan lebih mudah berbanding dengan membuktikan kehalusan hujah mereka yang dipandu oleh wahyu dan terpakai pada sepanjang zaman. Lagi, untuk mendakwa semua agama sebagai benar lebih mudah berbanding dengan membuktikan kebenaran satu-satunya agama yang diwahyukan, iaitu Islam. Dan menjustifikasikan kebebasan sebagai prinsip dan polisi tertinggi lebih mudah berbanding dengan penguatkuasaan kebenaran dalam bentuk undang-undang.
Oleh itu, idea-idea mudah dan asasi lebih mudah untuk “menang” di ruangan perdebatan awam berbanding dengan idea-idea rumit. Malangnya, idea yang mudah tidak selalunya secara automatik menjadi idea yang paling relevan dan terpakai dalam semua situasi. Sebagai contoh, sebuah negara tidak dapat ditabdir hanya dengan kefahaman demokrasi yang asasi. Sebaliknya, hal tersebut perlu dirumuskan ke peringkat yang lebih mendalam dan rumit sehingga mampu menghasilkan jentera institusi yang menggerakkan pentadbiran negara.
Begitu juga, Islam tidak mungkin kekal relevan selama lebih 1400 tahun dan subur di seluruh dunia jika kefahaman yang mendasarinya bersifat sangat asasi. Sebaliknya, ratusan ribu cerdik pandai sepanjang zaman telah menghasilkan pelbagai karya agung untuk mengulas hikmah Islam yang tidak kunjung habis, menjadikannya relevan di semua tempat dan masa.
Keempat, “idea lawan idea” yang tidak berhaluan juga membazirkan masa dengan perdebatan yang tidak produktif kerana idea palsu yang sama akan kerap timbul semula. Masa dan tenaga para ilmuwan akan dibazirkan untuk berlawan hujah dengan idea yang sudah terbukti batil. Oleh itu, bukanlah kesetiaan kepada tradisi keilmuan Islam yang memundurkan umat Islam, tetapi ironinya kebebasan berfikir yang tidak terpandulah yang masih menghambat kita daripada terus mara ke hadapan.
Maka itu, apakah penyelesaian kita? Di sini, Imam al-Ghazali telah pun menyediakan jawapannya dalam Nasihat al-Muluk. Secara asasnya, pemerintah harus memainkan peranan utama kerana melibatkan ruang awam dan kebajikan akidah masyarakat Muslim. Menurut beliau, pemerintah wajib menunaikan empat tanggungjawab, iaitu menghapuskan ajaran sesat daripada kerajaannya, memakmurkan kerajaan dengan kerjasama rapat bersama cerdik pandai, memelihara orang berpengalaman serta menimbang pengalaman mereka, dan mengurangkan kadar jenayah.
Pemerintah harus bekerjasama dengan ulama untuk menyelia ruang awam dan idea yang berlegar dalam ruang tersebut. Pemerintah tidak seharusnya membiarkan “padang” ruang awam “bebas” diragut oleh sesiapa sahaja. Sebaliknya, iktibar harus diambil daripada hadis Rasulullah SAW yang mengumpamakan pemimpin seperti penggembala. Kalimah rakyat yang berasal daripada kalimah Arab ra‘iyyah pula mengandungi dua makna, iaitu warganegara dan haiwan gembalaan. Kita dapat lihat bagaimana rakyat diumpamakan sebagai haiwan gembalaan yang tidak selalunya arif tentang keutamaan kebajikan mereka sendiri.
Rasulullah SAW mengingatkan lagi bahawa seorang Muslim tidak boleh menganiayai mahupun mengabaikan Muslim yang lain. Oleh itu, tidak seharusnya pemerintah mengabaikan rakyatnya dan membiarkannya menentukan “kebenaran” dan “nilai moral” untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus dididik dengan ilmu yang benar. Selain itu, rakyat juga harus dipersiapkan dengan pendidikan tasawuf secara sistematik dan tidak membiarkan usaha tersebut hanya digiatkan oleh masjid dan badan persendirian.
Kesimpulannya, artikel ini tidaklah sebulat-bulatnya menafikan pendekatan “idea lawan idea” di ruangan awam. Benar, terdapat merit yang harus dipertimbangkan. Namun demikian, jika dibiarkan untuk bergerak sendiri, pendekatan tersebut hanya akan membawa kepada kekeliruan massa dan merudumnya mutu pemikiran dan moral sesebuah tamadun.